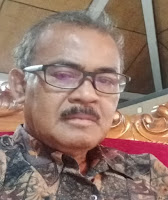|
| Pramoedya Ananta Toer, sastrawan legendaris Indonesia. |
Mediaberita6 - Sastrawan Pramoedya Ananta Toer, adalah pengarang andalan zaman Orde Lama. Tiba-tiba jatuh ke titik nadir, seiring dengan gagalnya kudeta G30S PKI, tanggal 1 Oktober 1965. Pram ditangkap oleh penguasa Orde Baru karena dianggap pendukung G30S. Dia dibuang ke Pulau Buru, Maluku bersama Rivai Avin, Buyung Puradisastra dan sutradara film Basuki. Prammodya sebagai pengurus Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) merupakan organisasi di bawah PKI terkena imbas dari tragedi kemanusiaan 1965.
_p136.jpg) |
| Pramoedya Ananta Toer |
Pram lahir tanggal 6 Pebruari 1925 di Blora Jawa Tengah, meninggal 26 April 2006. Berkat jasa-jasanya di bidang sastra, tahun ini diperingati 100 tahun Pramoedya, di berbagai daerah. Pram tetap kosisten di bidang sastra. Karyanya dikait-kaitan dengan gagasan realisme sosialis, ala Lekra. Ia mendapat tekanan politik yang cukup keras akhirnya dipenjarakan di Pulau Buru, selama 10 tahun dari tahun 1969-1979. Status sebagai tahanan juga dialami Pram sebelumnya, tiga tahun dalam penjara kolonial Belanda dan satu tahun di zaman Orde Lama.
Perhatian Dunia
Kehidupan Pram bersama tahanan politik lainnya di Pulau Buru, mendapat perhatian dunia internasional. Palang Merah Internasional sempat berkunjung ke tempat itu dan sangat prihatin karena lokasi itu tidak layak untuk kehidupan manusia. “Belasan tahun mereka hidup dalam pulau yang gelap gulita dengan kehidupan yang tidak normal. Makan cari sendiri, apa yang ada di pulau itu, sehingga para tahanan banyak yang meninggal karena kelaparan dan mengidap berbagai penyakit, kata Pram (Oyon dalam Warta tahun VI, no 2. Maret-April 2005)
Pram menuturkan, “kami betul-betul hidup dalam alam yang mengerikan, Kami dibuang begitu saja tanpa diberi bahan makanan atau diadili. Untung saja tidak beberapa lama kemudian datang rombongan Palang Merah Internasional berkunjung ke pulau itu. Mereka geleng-geleng kepala tentang sikap pemerintah Indonesia yang tidak menusiawi karena melakukan mereka seperti binatang. Dilepas di sebuah pulau yang tidak pernah dijamah orang. Para tahanan tidak dibekali makanan. Setelah rombongan itu meninggalkan Pulau Buru, baru besoknya makanan datang kepada kami. Padahal banyak dari tokoh- tokoh partai itu tidak ditangkap, dan sebaliknya banyak di antara kami yang bukan anggota partai dipenjarakan, Ini betul-betul dosa besar Orde Baru kepada bangsanya,”ujar Pram seperti dikutip Oyon dalam Warta tahun VI, no. 2 Maret-April 2005.
 |
| Buku-buku Tentang Pramoedya |
Atas desakan dunia internasional, Panglima Komandan Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) Jenderal Soemitro, ketika itu mengunjungi daerah tersebut untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan tahanan. Tujuan kunjungan itu supaya dapat merumuskan kebijakan baru menangani nasib tahanan politik. Pangkopkamtib mengajak rombongan wartawan seperti Mochtar Loebis, Sabam Siagiaan, Rosihan Anwar, psikolog Fuad Hassan dan sosiolog Saparinah Sadli (Horison, 2006).
Sebelum pulang ke Jakarta, Jendral Soemitro mengajak Pram di duduk di sebuah Teluk di sudut Pulau Buru. Sumitro berbincang, apa saja alasan Pram masuk Lekra. Pram menjawab, alasan memperjuangkan kemanusiaan. Soemitro terkesan dengan Pram. Ia pun bertanya, “Apa ada yang bisa saya bantu,” Pram menjawab, kalau boleh saya minta mesin ketik, kertas, karbon, notes, juga kamus dan buku-buku berbahasa Perancis,”. “Baik saya usahakan, “ jawab Soemitro. Dialog singkat itu dikutip Wahyudi (2019 : 30) dalam buku, Pramoedya Ananta Toer Kisah Di Balik Bumi Manusia.
Beberapa hari kemudian Jendral Soemitro memenuhi janjinya. Soemitro atas perintah Presiden Soeharto menyerahkan mesin ketik untuk dipakai mengetik tulisan-tulisannya. Dalam serba keterbatasan itu, Pram menulis dalam kertas semen bekas dan menggunakan alat tulis seadanya. Walaupun hidup dalam tahanan di Pulau Buru, Pram tetap berkarya menghasilkan novel tetralogi Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Rumah Kaca dan Jejak Langkah. Novel tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh sastrawan Australia, Max Lane. Novel-novel tersebut akhirnya tersebar luas di seantero dunia. Selama di Pulau Buru, Pram juga sempat menulis novel yaitu Arok Dedes, Arus Balik, Mata Pusaran dan Mangir. Ditambah satu karya nonfiksi berjudul Nyanyian Tunggal Seorang Bisu.
Pelarangan Buku
Pemerintahan Orde Baru melakukan pelarangan massal terhadap buku dari hasil pengarang yang diduga terlibat G30S. Pihak yang mengeluarkan intruksi pelarangan ini adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Kejaksaan Agung. Kedua lembaga itu dalam melaksanakan instruksi menemui kendala di lapangan. Menurut perhitungan beberapa penulis yang dikutip Tim Jaringan Kerja Budaya, jumlah buku yang dilarang sampai tahun 1970, menacapi 2000 judul. Angka itu sendiri tidak dapat dipastikan karena dokumentasi tentang proses pelarangan tidak tersedia lengkap. Di samping itu, muncul tumpang tindih wewenang lembaga-lembaga kontrol dalam menjalankan instruksi Mendikbud. Selanjutnya pemerintah melalui Jaksa Agung Nomor Kep.052/JA/5/1981, melarang peredaran novel Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa, karya Pramoedya. (Tim penulis Jaringan Kerja Budaya, 1999)
Kedua novel tersebut dinilai bertentangan dengan Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1996 tanggal 5 Juli 1966 terkait Pembubaran Partai Komunis Indonesia, sebagai orgaisasi terlarang. Dua buku tersebut, setelah dipelajari secara seksama dan kelincahan pena pengarangnya serta halus dan terselubung melalui data-data sejarah, telah menyusupkan ajaran Marxisme dan Lenimisme. Tidak saja kedua novel Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa, karya Pramoedya yang lain, novel Rumah Kaca dan Gadis Pantai juga dilarang beredar melalui Keputusan Jaksa Agung No. 061/J.A./1988.
Kejaksaan menyita novel Bumi Manusia yang ada di toko dan agen buku. Sebagian orang yang punya novel ini menyerahkan ke kejaksaan secara sukarela, takut berurusan dengan aparat. Tapi,menurut Wahyudi (2019 : 50), dari 20 ribu novel yang dicetak penerbit Hasta Mitra, tak sampai seribu buku yang berhasil disita. Selebihnya tetap menjadi koleksi milik pembaca. Ini artinya, banyak pembaca yang tertarik terhadap isi novel tersebut. Rasa ingin tahu ini bisa juga disebabkan karena kehidupan Pram yang penuh kontroversi, sehingga masyarakat menolak menyerahkan novel tersebut ke pihak berwajib.
 |
| Pramoedya pada 1990-an |
Sarjana Belanda, Teeuw (1997 : 3) mengatakan, praktis semua karya sastra Pramoedya mempunyai latar kenyataan yang cukup mantap, pertama-tama kenyataan hidupnya sendiri, lahir dan batin, kenyataan orang di sekitarnya, kenyataan masyarakat Indonesia sezaman dan akhirnya kenyataan sejarah. Berlandaskan konsep tersebut, Teeuw akhirnya berhasil menulis buku yang cukup tebal (428 halaman) tentang Pramoedya berjudul, Citra Manusia Indonesia dalam Karya Pramoedya (1997). Dalam analisis buku itu, Teeuw mengupas karya-karya Pramoedya dengan model chek and recheck antara cerita, tokoh, latar dengan biografi Pramoedya sejak kecil sampai statusnya sebagai tahanan politik.
Rezim sudah berganti, zaman sudah berubah. Tidak ada lagi alasaan untuk tidak mengakui kebesaran sastrawan Pramoedya. Apalagi Pramoedya, satu-satunya sastrawan Indonesia sampai kini beberapa kali masuk nominator penerima Hadiah Nobel di bidang sastra. Di dalam negeri, sastrawan ini sempat dimarginalisasi, namun di luar negeri mendapat pujian seperti Max Lane (Australia), Teeuw, Boef dan Snock (Belanda), Katrin Bandel (Perancis), Yayasan Magsaysay (Fhilipina), dan sekolah-sekolah di Malaysia. Bahkan novel Pram, Keluarga Geriya dijadikan buku bacaan wajib para pelajar Malaysia selama bertahun-tahun. Berkat jasa Max Lane, tetralogi Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah dan Rumah Kaca bisa mendunia. (Editor : Guntur S)